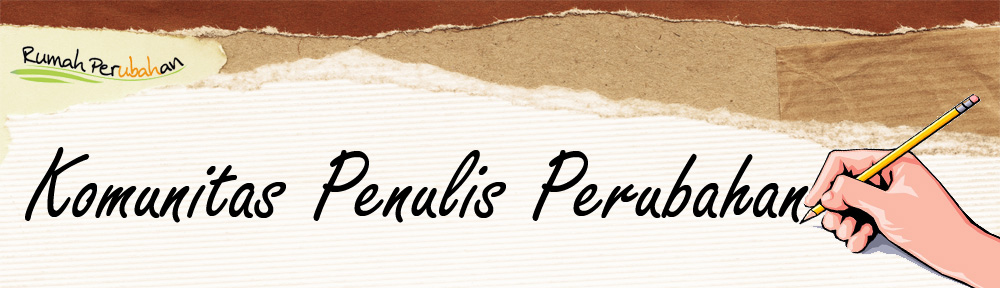Setiap kali memasuki masa Ujian Nasional (UN), bangsa ini heboh. Sebelum ujian heboh, setelah ujian juga gaduh. Dengan dalih memberi motivasi, guru-guru malah membuat anak-anak stres dan bersedih menjelang UN. Orang tua dipanggil, anak menangis karena suasana yang dibangun para guru adalah para murid itu “banyak dosa” dan telah melakukan kesalahan pada orangtua. Alhasil bukannya plong, malah banyak murid yang mengalami histeria yang disebut “kesurupan” atau “kerasukan” setan.
Mengapa ujian nasional menjadi segala-galanya dalam hidup ini? Apakah tidak ada cara lain untuk membuka pintu masa depan anak selain ujian?
Saya ingin mengajak bangsa ini keluar dari metode pendidikan cara pabrikan yang menghasilkan “produk-produk” yang standar, yang seakan-akan anak adalah “output” hasil produksi. Kita seperti sedang melewati sebuah area “ban berjalan” dengan seorang manajer Jepang, yang mengawasi ada-tidaknya produk yang cacat (defect), di luar standar.
Mereka yang berada di luar standar itu dalam pendidikan kita sebut “berbakat khusus” (special talent), namun di pabrik kita sebut “produk gagal”. Jelajahilah mesin pencari Google dan ketiklah kata “special talent”, maka Anda akan menemukan anak-anak seperti inilah yang ditawari beasiswa. Namun apa yang kita lakukan dengan anak-anak itu di sini?
Kecakapan Bakat
David McClelland pernah menyatakan bahwa suatu bangsa harus dibangun dengan sistem kecakapan, bukan kekerabatan, apalagi didasarkan warna kulit atau sentimen-sentimen kesamaan lahiriah. Sistem kecakapan itu mulai diperbincangkan oleh Confucius, diterapkan oleh Dinasti Han di China pada abad ke 2 SM, dan dibawa ke dunia barat, lalu disebarkan ke seluruh dunia.
Pada awal peradaban modern, manusia yang dulu percaya pada kecakapan otot beralih ke kecakapan intelegensia (IQ). Di era world 1.0, saat lapangan pekerjaan terbesar hanya bisa diberikan oleh negara, sistem kecakapan dipersandingkan antara IQ dengan ujian pengetahuan. Demikianlah generasi tua Indonesia mengikuti ujian seleksi masuk Universitas Negeri atau seleksi menjadi PNS melalui pemeriksaan kecapan tertulis. Yang diuji adalah rumus-rumus, mulai dari bahasa, IPA, matematika, hingga Pancasila. Rumus-rumus itu dihafalkan dituangkan pada kertas. Sedangkan sekolah swasta dan dunia usaha memilih kecakapan intelegensia.
Ujian tertulis dengan ujian pengetahuan menjadi penting karena jumlah pesertanya massal dan negara harus bertindak secara adil. Negara adalah segala-galanya.
Tetapi itukan dulu. Sekarang ini pilihan masyarakat sudah begitu luas. Pekerjaan bukan hanya ada di pemerintahan, dan sekolah tinggi yang bagus bukan hanya Universitas Negeri. Masyarakatnya boleh memilih, mau hidup di world 0.0, atau menjadi pengusaha global, konsultan, seniman atau professional di world 2.0 (globalisasi dini) atau world 3.0 (lihat kolom saya: Empat Dunia Yang Membingungkan).
Artinya masyarakat bangsa ini tak menggantungkan lagi kehidupannya untuk menjadi PNS. PNS bukanlah segala-galanya. Dunia ini sendiri begitu terbuka, penuh kesesakan dan pilihan, bahkan persaingan dan saling melengkapi. Dunia yang sesungguhnya itu bukan membutuhkan kecakapan ujian, melainkan kecakapan-kecakapan impak, yaitu apa yang sebenarnya dapat dilakukan seseorang dari pendidikan yang ditempuhnya. Kalau seseorang belajar tentang pertanian, maka ia bisa buat apa dengan ilmunya itu? Kalau ia belajar membuat robot, apa impak yang bisa diperbuat? Kalau sekolah kedokteran, bisakah berkiprah di sektor kesehatan? Demikian seterusnya.
Kecakapan seperti ini disebut kecakapan bakat (talent merit) dan pernah merisaukan Mendiknas Singapura 20 tahun lalu saat negara merasa segala-galanya. Sekarang ini Singapura telah beralih ke sistem kecakapan bakat yang memungkinkan anak-anak menemukan pintu masa depannya dengan lebih damai dan lebih membahagiakan.
Untuk memberikan ilustrasi, saya ceritakan kembali pengalaman saya saat mengajar mata kuliah “International Marketing”. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa senior di Program S1 dan sebagai prasyaratnya mereka harus sudah lulus “Dasar-Dasar Marketing”. Suatu ketika saya iseng menanyakan berapa mahasiswa yang mendapat nilai A di kelas marketing yang diambil satu dua semester sebelumnya, dan saya minta mereka maju kedepan. Dan sungguh saya tak percaya bagaimana anak-anak yang kurang bergaul, kurang pandai mengekspresikan pikiran, bahkan dikenal sebagai anak yang berbicara sinis, dan berpenampilan tidak “marketable” dari kacamata rekan-rekannya, bisa diberi nilai A.
Begitulah “the power of exam merit”. Mereka mendapatkan nilai “A” dalam transkrip nilai karena bertemu dengan pengajar-pengajar yang hanya berorientasi pada hasil ujian, bukan pendidik yang mengubah cara mereka berpikir. Di atas kertas pada saat ujian mereka benar-benar cerdas, hafalannya bagus, analisisnya ok, tetapi mengapa untuk hal sederhana saja tak mampu mengaplikasikan pengetahuannya? Saya jadi teringat kisah seorang teman yang belajar bahasa Inggris di Amerika Serikat supaya bisa kuliah S2 di Amerika. Belajar bahasa Inggris di masyarakat yang berbahasa Inggris kok di kamar memakai headset?
Kalau demikian cara kita mendidik anak-anak ini, maka bisa saya bayangkan mengapa pengusaha mengeluh lulusan-lulusan kita tidak siap pakai, dan mengapa terdapat gap besar antara pilihan sekolah dengan pilihan profesi. Anak-anak mengeluh sekolahnya susah karena mereka tidak bisa mengekspresikan bakat yang mereka cintai. Guru mengeluh murid-murid tak mempersiapkan belajar di rumah dengan baik. Orang tua mengeluh anak-anaknya menjadi pemberang. Dan tentu saja di masa depan, dari sistem pendidikan seperti ini hanya akan dilahirkan sarjana-sarjana kertas, atau ilmuwan-ilmuwan paper, yang hanya asyik membuat makalah, bukan impact!
Rhenald Kasali
Founder Rumah Perubahan