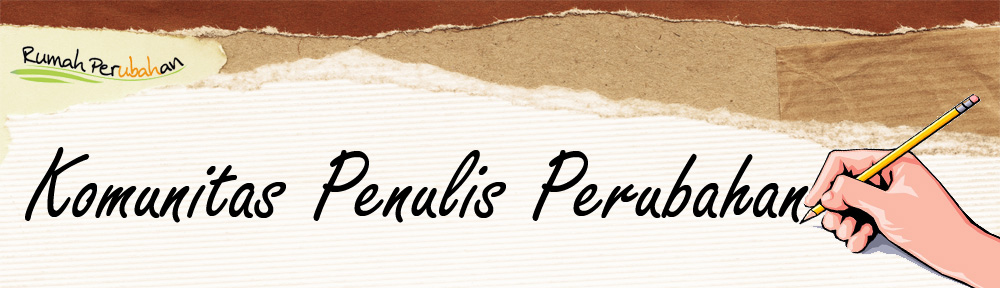Saya baru saja kembali dari pesisir Timur Aceh, menelusuri jalan darat dari Lhokseumawe, melewati Bireun, Desa Matang yang terkenal dengan satai lembunya, terus ke atas hingga dataran tinggi di Takengon dan kembali lagi ke Bireun, lalu menembus Sigli dan masuk Ke Banda Aceh.
Berbeda dengan kondisi jauh sebelum Tsunami yang kondisi jalannya buruk, maka kini Aceh telah menjelma menjadi provinsi dengan jaringan infrastruktur terbaik Indonesia. Kondisi jalan berkualitas tinggi yang dibangun dengan dana bantuan internasional, lapangan terbang, pelabuhan, rumah sakit bantuan asing, perumahan rakyat yang dibangun dengan perencanaan yang matang yang dipimpin putra terbaik Indonesia: Prof. Kuntoto Mangkusubroto. Kawasan pelabuhan bebas Sabang juga mulai bergeliat, setelah proses rekruitmennya berhasil mengedepankan merit system. Ir. Fauzi Husin, mantan presiden PT. Arun sudah aktif bekerja, dan beberapa rombongan kapal pesiar sudah singgah di sana.
Ternyata benar nikmat menjadi Jokowi. Nikmatnya blusukan benar-benar saya rasakan. Bahkan mungkin lebih nikmat dari pada menjadi gubernur karena saya bisa melakukan apa saja tanpa pengawasan kamera televisi, atau kawalan birokrat yang mengatur perjalanan. Blusukan versi saya ini murah meriah. Tetapi sampai di dataran tinggi Gayo saya harus kecewa: Tak ada kedai kopi yang besar, seharum nama kopinya yang terkenal seantero jagad raya ini. Hanya ada kedai nasi biasa yang menjual kopi seperti di pasar tradisional lainnya, dan hanya ada kebun-kebun kopi yang bijinya dijemur di jalan-jalan raya.
Mana Wirausahanya?
Semua pejabat tinggi Indonesia berbicara tentang kewirausahaan, dan semuanya berbicara tentang pentingnya infrastruktur. Tetapi dua-duanya jalan sendiri-sendiri. Yang satu bicara infrastruktur terus, yang satunya kewirausahaan terus. Yang mengorkestrasi keduanya praktis tidak ada. Contoh kasusnya bisa dilihat di Aceh: infrastrukturnya bukan saja baik, melainkan yang terbaik, tetapi ekonominya masih mengandalkan sekor-sektor tradisional.
Industri besar belum masuk. Sebagian besar perekonomiannya masih sangat mengandalkan perdagangan dari kota Medan. Kalau di era BRR banyak serpihan usaha kontraktor yang bisa diambil, kini sudah tidak ada lagi. Perdagangannya masih sama, dijalankan orang-orang asli Sigli yang sejak dulu dikenal ulet dan rajin merantau. Kedai Kopi yang dulu jumlahnya terbatas, kini tambah banyak tetapi di pusatnya di Gayo malah tak terlihat. Sedangkan bisnis rempah-rempah masih berjalan seperti dulu. Belum tampak industri baru yang dulu benar-benar diniatkan pemerintah pusat seperti yang dilakukan di era Soeharto.
Harap maklum, kewirausahaan ekonomi rakyat belum banyak bergerak. Kewirausahaan baru menjadi “mainan” indah anak-anak muda di Pulau Jawa dan kota-kota besar tertentu yang kampusnya dipimpin rektor-rektor yang tepanggil. Sebut saja UGM, ITS, ITB, dan IPB. Maka tak heran kalau konsentrasi wirausahawan muda Indonesia masih terkonsentrasi di Bandung, Jogja, Malang, Surabaya, Makasar dan Denpasar. Lalu perlahan-lahan mulai menggema di Medan, Palembang, dan Pontianak. Selebihnya ia masih menjadi wacana yang indah ketimbang sebuah gerakan yang benar-benar terstruktur.
Kembali ke Aceh, harap maklum pada tahun 2014 gas yang disedot dari ladang kaya di Lhokseumawe akan habis dan PT. Arun akan berhenti beroperasi, kecuali pemerintah serius menyelamatkannya. Kalau gasnya habis, Pupuk Iskandar Muda akan ikut berhenti beroperasi, mengikuti saudaranya: Asean Aceh Fertilizer yang sudah lebih dulu dibiarkan menjadi besi tua. Kita akan bahas khusus turn-over PT. Arun minggu depan. Tetapi tanpa keseriusan membangun wirausaha ekonomi kerakyatan, saya kira sulit bagi Indonesia menurunkan tingkat ketimpangan sosialnya. Rakyatnya hanya akan bertarung memperebutkan pekerjaan dan koneksi melalui Pilkada, lalu beramai-ramai melakukan intervensi politik terhadap unit-unit ekonomi milik pemerintah daerah maupun pusat. Sedangkan kekayaan yang sebenarnya tak ada yang menyentuhnya.
Tak adanya kedai kopi yang memadai di Takengon atau kedai-kedai kopi yang dibangun orang Takengon di kota-kota lain di Provinsi Aceh adalah salah satu indikasinya. Bank-bank pembangunan daerah belum cukup terpanggil untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan yang naik kelas dan dikelola secara profesional. Mereka masih menutup mata menyaksikan kedai-kedai ekonomi milik rakyat yang kini diserbu kalangan berpendidikan yang menawarkan grobakchise-grobakchise yang dijajar di kaki-kaki lima. Wirausaha baru tanpa visi itu dibiarkan menjadi kompetitor berat ekonomi rakyat yang berbisnis “as ussual”. Jelaslah grobakchise berlampu terang dengan “branding” yang lebih mencolok jauh lebih menarik bagi kaum muda ketimbang kerak telor yang dipikul Bang Miun, atau soto ayam Pak Kasdu yang tendanya sudah lusuh.
Singkatnya, tanpa wirausaha yang memadai, tanpa kewirausahaan, infrastruktur hanya akan jadi hiasan provinsi. Rakyat hanya punya impian bagaimana menjadi konsumen, bukan penggerak perekonomian. Peta yang demikian hanya akan mendorong partisipasi untuk korupsi ketimbang sebuah civil society yang sehat. Dan tanpa kesadaran itu, kita akan melaksanakan model yang sama di NTT, Papua, Maluku dan sebagian propinsi di Kalimantan dan Sulawesi.
Rhenald Kasali
Founder Rumah Perubahan