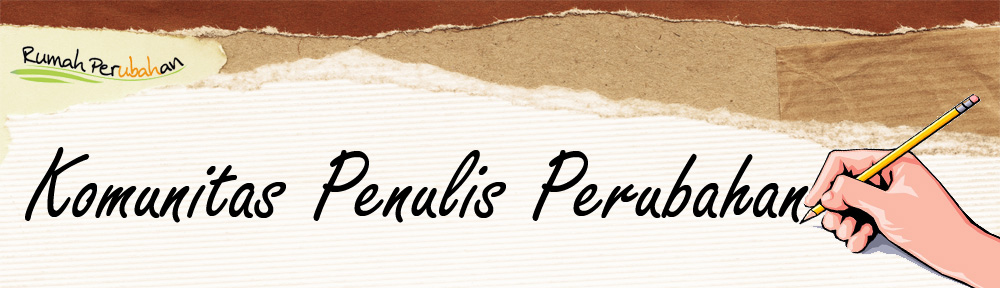“Change will not come if we wait for some other person, or if we wait for some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.” Barrack Obama.
Tak dapat disangkal bahwa saat ini banyak orang menyenangi kata perubahan. Tetapi apakah mengerti konsekuensi-konsekuensi dari perubahan? Rasanya belum tentu. Masih banyak orang yang berpikir “Change” atau Perubahan adalah “ganti orang”, atau ganti pimpinan. Maka tak heran kata perubahan bukan cuma laku dalam dunia usaha, melainkan juga dalam pilkada atau pemilu.
Dan kalau dibawa ke ranah itu, hampir pasti perubahan dibaca dari sisi politik. Atau bisa jadi kaum profesional yang sedang melakukan transformasi berpotensi menjadi korban politisasi. Lagi asyik melakukan transformasi yang bukan main banyak musuhnya, malahan dapat “musuh baru”, yaitu kandidat pejabat publik yang butuh suara. Mengapa begitu?
Selalu Ada Resistensi
Saya kira publik sudah semakin cerdas dan mengerti bahwa perubahan selalu berhubungan dengan adanya “kelompok yang melawan”. Kaum resisten ini jumlahnya tidak banyak, tetapi mereka sangat vokal dan berjuang agar tidak kehilangan. Di bumi yang perasa, orang yang pernah menduduki posisi terhormat bila kehilangan jabatan karena tidak lolos fit and proper test bisa berarti kehilangan muka.
Dan “kehilangan muka” bisa berarti “tsunami” bagi pelaku-pelaku transformasi. Padahal transformasi tidak bisa jalan bila tidak mendapatkan energy yang kuat. Transformasi butuh suasana persatuan dan kepercayaan.
Banyak orang yang tak menyadari bahwa setiap langkah transformasi sangat beresiko bagi jabatan seseorang. Kalau hanya kehilangan kursi saja itu belumlah seberapa. Dalam banyak kasus, kelompok yang resisten tidak hanya mengungkit kursi, melainkan mencari cara untuk menemukan kesalahan-kesalahan kecil yang bisa diperbesar. Padahal dalam era VUCA, manusia bekerja dalam iklim yang complex dan mudah mengambil langkah yang salah, lupa atau ada saja kekurangannya.
The Burning Platform
Dalam buku ChaNgE! yang saya tulis tahun 2005, Robby Djohan memberikan kata pengantarnya. Ini mungkin kata pengantar terpendek yang pernah saya terima, tapi isinya sungguh mengena pada sasaran. Saya kutipkan saja sebagian: “Perubahan adalah bagian yang penting dari manajemen dan setiap pemimpin diukur keberhasilannya dari kemampuannya memprediksi perubahan dan menjadikan perubahan tersebut suatu potensi.”
Lalu, pada alinea kedua Robby menulis catatan yang menurut saya sangat penting bukan saja karena pengakuannya yang jujur, tapi memang sering kita alami: “Sering kali seorang CEO, termasuk saya sendiri, berhadapan dengan perubahan setelah dia sudah berada di ambang pintu. Situasi seperti ini mungkin dapat diatasi, tetapi hasilnya pasti bukan sebagai suatu potensi ataupun kegunaan.”
Robby memang selalu bicara to the point.
Perubahan, bagi sebagian kita, adalah sesuatu yang menakutkan. Namun, manakala kita berhasil mengendalikan rasa ketakutan itu, perubahan menjadi energi yang luar biasa untuk membuat kita bangkit kembali. Namun manakala kita kalah, maka betapa bisingnya suara di luar. Apalagi bila anda melakukan perubahan pada lembaga yang ada hubungannya dengan negara, milik negara atau milik pemerintah daerah. Anda akan menyaksikan banyak “peluru nyasar” yang tidak jelas hendak ditembak kemana. Perhatikan saja betapa “bisingnya” keributan di seputar Bank BJB yang muncul justru pada saat pemungutan suara. Itupun bisa jadi ajang perpecahan sesama aktivis yang mulanya sama-sama mau memberantas korupsi. Ada peluru yang ditujukan pada salah satu kandidat, meski informasi awalnya mungkin berasal dari orang dalam yang ditujukan pada salah satu calon direksi yang jabatannya diinginkan orang lain. Lalu ada lagi peluru yang disasarkan kepada CEO. Penembak yang lihay ternyata juga tak bisa menembakkan peluru ke sasaran yang tepat karena begitu masuk ke ranah politik, masing-masing pihak punya kepentingan yang berbeda dan sulit dikendalikan. Akhirnya tsunami terjadi betulan, bukan hanya change maker yang terlibat, melainkan juga lembaganya akan sulit dibangun kembali.
Belajar dari berbagai perubahan yang dilakukan di sejumlah lembaga publik maupun BUMN besar yang rumit, kemudian mengingatkan saya pada sosok panglima perang yang terkenal dalam sejarah Islam, Thariq bin Ziyad. Kisahnya kurang lebih begini.
Thariq yang lahir sekitar tahun 670 Masehi dibesarkan kabilah Nafazah di Afrika Utara. Perawakannya tinggi, keningnya lebar dan kulitnya putih kemerahan. Thariq adalah murid seorang komandan perang di Afrika Utara yang dikagumi karena kegagahannya, kebijaksanaannya dan terutama keberaniannya.
Suatu ketika seorang pangeran Spanyol, Julian, meminta bantuan pembimbingnya untuk menaklukkan Raja Roderick yang berkuasa di Spanyol. Lalu, Thariq diutus untuk mengintai kekuatan bangsa Visigoth dan menjajaki kemungkinan pengiriman pasukan dalam jumlah besar.
Akhirnya, waktunya pun tiba. Ketika Raja Rodercik sedang sibuk menghadapi pemberontakan di kawasan utara kerajaannya, Thariq datang dengan 7.000-an prajuritnya untuk menyerbu Spanyol. Pengiriman pasukan dilakukan melalui laut. Pasukan ini mendarat di dekat gunung batu besar yang kelak dinamai Jabal (gunung) Thariq. Orang-orang Eropa menyebutnya Gilbraltar.
Ketika sampai di Spanyol, Thariq mengambil keputusan yang sangat mengejutkan seluruh prajuritnya dan dikenang sebagai langkah fenomenal hingga saat ini. Ia membakar semua perahu yang digunakan untuk mengangkut para prajuritnya. Para prajuritnya tentu saja terperangah. Kaget, dan sebagian bahkan marah.
Setelah membakar semua perahu, Thariq berdiri di hadapan prajuritnya dan berkata, “Di mana jalan pulang? Laut ada di belakang kalian. Musuh ada di depan kalian. Mereka sudah siaga. Sementara, kalian tidak memiliki bekal lain kecuali pedang, tidak ada makanan kecuali yang dapat kalian rampas dari tangan musuh-musuh kalian.”
Dalam ilmu manajemen, apa yang dilakukan Thariq dikenal dengan istilah the burning platform. Dan, itu pulalah yang dilakukan para change maker yang piawai kala dipercaya memimpin Transformasi. Kebanyakan pemimpin mau tak mau harus menciptakan kondisi yang membuat semua orang tidak punya pilihan lain, tidak bisa mundur lagi, sama seperti yang Thariq lakukan. Kalau mau bertahan hidup, Thariq dan para prajuritnya hanya punya satu pilihan, yakni maju terus.
Begitu pula yang terjadi dengan kebanyakan perusahaan milik negara yang sarat politisasi. Kalau para karyawannya ingin bertahan hidup, maka mereka harus maju membenahi bersama. Hanya itu pilihannya. Masalahnya, apakah para aktivis kebijakan publik mengerti bahwa mereka bisa dipakai kaum resisten untuk menaburkan peluru amarah mereka yang sedang kehilangan muka? Pilihannya hanya dua: bersekutu dengan the losers yang resisten, atau memperkuat the winners agar menghasilkan transformasi yang berujung kebaikan. Atau mungkin mereka berpikir ada opsi ketiga yang kita tak pernah tahu apa itu. Kala keributan menjadi mahal, maka semua ada ongkosnya, dan tentu saja ada tukang catutnya.
Rhenald Kasali
Founder Rumah Perubahan