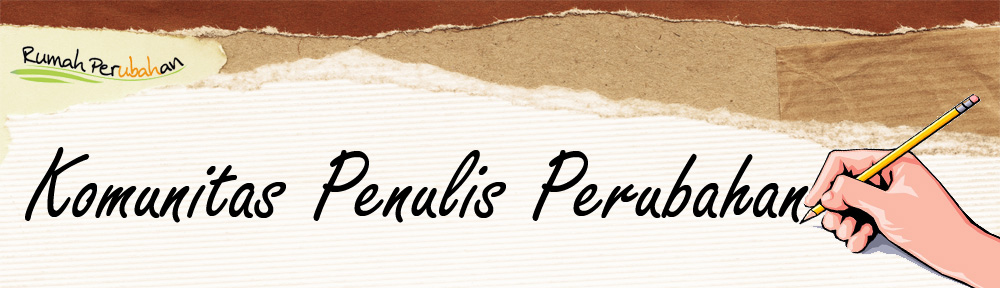Di atas panggung di sebuah gedung opera cerita rakyat di Beijing, seorang pria tampak sibuk bersolek. Rekan saya dari Universitas Renmin berbisik, “Dia itu badutnya, bukan guru yang menjadi inti cerita.” Namanya Habei. Wajahnya murung. Tetapi begitu kamera mengarah kepadanya, ia terlihat riang dan mulai melucu. Rekan saya yang lain, profesor dari Universitas Dublin yang keturunan Irlandia berujar serius: Impresif! Tetapi anehnya ia sama sekali tidak tertawa.
Padahal batin Habei penuh luka, bisik rekan saya lagi. Menurut plot cerita, Habei datang ke kota dengan impian menjadi orang terpandang. Di sana, Ia diterima di sebuah sekolah guru. Meski bukan angan-angannya, Habei tak pula membanting setir. Tak cukup nyalinya untuk bertarung mengejar ilmu yang lebih menantang. Karena terikat kontrak, begitu lulus, Habei kena wajib mengajar. Namun ia tak senang dengan upah rendah sebagai abdi negara.
Setelah itu ia diterima mengajar di sebuah sekolah internasional. Tapi karena tak sepenuh hati, Habei diberhentikan. Kinerja mengajarnya buruk. Maka jadilah Habei pemain opera. Ia diterima menjadi badut karena itulah satu-satunya pilihan yang tersedia. Lagi pula kata-katanya sinis, sulit dijadikan manajer. Tetapi siang hari ia bisa menyambi menjadi makelar atau konsultan paruh waktu untuk lembaga-lembaga donor.
Kata rekan saya, Habei ini hanya berani melucu kalau wajah aslinya ditutupi bedak. Di dunia riil nya, Habei adalah pendiam dan penakut.
Setiap malam ia kebagian peran pembuka selama lima menit. Bersolek menghias muka dengan pupur dan bedak aneka warna. Berceloteh sejenak tentang pendidikan, lalu menghilang. Lalu munculah cerita yang ditunggu-tunggu tentang guru, mirip Laskar Pelangi. Namun karena ceritanya menarik, nama Habei ikut terangkat. Ia juga suka memberi komentar di media jejaring sosial China: http://www.weibo.com/. Bahasanya khas: sinis, negatif, dan terkesan ada luka besar dalam jiwa yang berasal dari kisah hidupnya yang tak sesuai dengan impiannya. Dalam literatur pendidikan, diketahui orang-orang yang sinis memiliki otak bagian depan yang mengerucut yang sebenarnya mencerminkan ketidakcerdasannya menafsirkan konteks.
Jaringan atau Kemitraan
Habei tidak hadir seperti badut dalam opera “I Pagliacci” yang pernah populer di Italia di awal abad 20. Ia hanya hadir sesaat untuk memberi warna seadanya. Sedangkan dalam “I Pagliacci” yang digemari di Barat, badut tampil dengan peran yang dominan yang justru menjadi inti opera. Perbandingan itu menjadi asyik karena menjadi bahan diskusi sejumlah guru besar yang datang atas undangan Renmin University yang dikenal sangat berpengaruh di China dan menjadi motor pembaru ekonomi China dalam 20 tahun belakangan ini.
Renmin sejak awal aktif bersama MMUI dan Yale School of Management mengembangkan jejaring perubahan untuk memperbarui kurikulum pendidikan calon pemimpin. Di dalam jaringan ini juga terdapat Seoul National University, NUS -Singapore, INSEAD, London School of Economics, Hitotsubashi University (Jepang), IE Madrid, dan 15 kampus lainnya. Berbeda dengan metode Kemitraan yang sudah berlangsung bertahun-tahun, kami lebih percaya pada bentuk jaringan. Maka, kelompok ini menamakan dirinya GNAM: Global Network for Advanced Management.
Karena berbentuk jaringan, maka aturannya dibuat bersama-sama, tidak ada aktor yang dominan meski negaranya lebih maju dan kampusnya memiliki reputasi dunia yang jauh lebih tinggi. Begitu diterima di MMUI misalnya, setahun kemudian mahasiswa kami berhak kuliah bareng para eksekutif global di Yale yang kalau ikut proses seleksi sendiri bukan main sulit dan mahalnya.
Melalui jejaring itu pula mahasiswa Yale berduyun-duyun datang ke Jakarta mendengarkan kuliah di MMUI. Kami mengembangkan immersion week yang kuliahnya bergilir di beberapa negara. Metode belajar memang telah jauh berubah yang menuntut anak-anak Indonesia lebih bersikap terbuka, lebih elaboratif dan assertive, bahkan lebih percaya diri.
Sejak awal kami sepakat bahwa model jaringan lebih baik daripada kemitraan asalkan semua pemimpin yang datang berpikir terbuka, aktif berpartisipasi dan berkontribusi, saling timbal balik, segala urusan dibuat simpel dan kurangi birokrasi. Jaringan ini dengan cepat menjadi contoh dalam model pengembangan sarjana yang berwawasan global, meski ia hanya datang dari negeri yang tak diperhitungkan.
Namun semakin digali, ada rasa was-was melihat bagaimana pendidikan dasar berlangsung di sini. Pendidikan dasar itu adalah fondasi yang menentukan lahirnya lulusan-lulusan terbaik universitas. Mereka adalah calon pemimpin yang kelak menjadi harapan bangsa. Di seluruh dunia, bangsa-bangsa besar sudah tuntas memperbarui diri, sementara kita masih ribut tiada henti. Mereka semua berani bereksperimen, mengalami kegagalan, lalu meremajakan diri dengan cepat.
Sementara di sini, bisingnya minta ampun. Semua orang menginginkan kesempurnaan dalam sekejab, tetapi begitu ada yang berani melakukan hal yang baru, langsung dipertanyakan.
Para pembaru pendidikan itu telah berupaya keras melahirkan sarjana-sarjana unggul yang siap ditempatkan dimana saja. Ketika sebuah ide muncul, mereka berebut menjadi role model dengan membuat contoh, sedangkan di sini semua orang berebut membuat organisasi untuk menyuarakan opini dan mencari proyek. Perubahan sulit sekali digulirkan karena miskin role model dan lebih banyak “badut” yang berebut panggung ketimbang guru yang benar-benar menjalankan apa yang ia ucapkan.
Namun benarkah sebuah transformasi bisa berlangsung mulus tanpa ujian? Semua sahabat saya yang berkumpul dalam Dean’s Conference mengenai jaringan ini di Beijing hari Senin-Rabu kemarin membantahnya. “Banyak kegagalan yang kami buat di tahap awal bahkan menjadi olok-olok di panggung Opera,” kata seorang dekan. Yang lain mengatakan, “kegagalan itu bisa menjadi pelajaran, tetapi yang mengambil pelajaran keliru karena tak mau melewati fase itu.”
Mereka semua sepakat, masa-masa sulit harus rela dilewati, bukan hanya dijadikan wacana atau ancaman. “Bahkan sebagus apapun sebuah model, Ia berpotensi gagal. Bukan karena modelnya jelek,” ujar dekan lainnya. Seorang eksekutif senior yang terlibat dalam proses pembaruan menambahkan, “sebagus apapun sebuah pembaruan, kalau semua orang hanya mampu melihat dunia baru dengan kacamata lama, yang muncul hanyalah keluhan dan kutukan.”
Badut dan Punakawan
Di TVRI, hari Selasa Kemarin. Dalang Sujiwo Tejo mengutarakan kegusarannya melihat ruwetnya masyarakat berpolemik. Ia mengambil seperangkat wayang yang terdiri dari para Punakawan dan memainkan karakter keempatnya. Ya seperti itulah masyarakat kita. Ada yang “membagongkan” diri (artinya ‘gemar membantah, asal ingin memberontak’ ), “berpetruk” (‘yang meninggalkan’, easy going) atau sedang “bergareng” (‘yang ingin berbeda’, mempertanyakan). Ada yang asal omong, asal usul, bahkan asal jepret.
“Yang hilang itu sosok Semar. Semar itu berasal dari kata Samara, yang artinya ‘ghaib’. Dialah sang moderator dari para Panakawan itu,” ujarnya. Mendiang Gus Dur, yang sesulit apapun selalu berani menghadapi ketiga karakter tadi, menurut Sujiwo adalah sosok Semar yang kini hilang. Maka jangan heran, ada banyak perubahan mendasar yang terjadi di eranya meski gonjang-ganjingnya banyak, ujungnya pembaruan.
Lucunya, rekan-rekan saya dari universitas di Barat juga percaya bahwa dalam perubahan selalu saja ada sosok punakawan, atau bahkan badut yang berpura-pura menjadi pembaru. Di Barat, pembaruan diyakini hanya akan terjadi kalau hadir pemimpin dengan determinasi yang kuat. Bahkan sekuat Margareth Tatcher pun tak ada masalah. Tetapi di Timur, banyak orang yang sulit menerima karakter yang keras.
Tetapi sekuat apapun kepemimpinan seorang pembuat perubahan, selalu ada yang memerankan badut dalam perubahan. Ia bisa menghibur, tapi juga bisa asal tampil. Bisa lucu atau beranggapan dirinya lucu. Yang jelas ia bukan pemeran utama. Badut yang pintar punya fondasi ilmu yang kuat, sedangkan badut yang bodoh hanya menjadi alat bagi dalang untuk menghibur. Ia hanya tampil kalau dalangnya mengirim tanda. Kalau dalangnya Semar ia bisa ngawur-ngawuran tapi bermain cantik, lucu, dan muaranya adalah pembaruan. Artinya, nilai tambah bagi sebuah tontonan perubahan.
Tapi kalau dalangnya Bagong atau Gareng, dan seseorang berperan “badut”, itu namanya supply ketemu demand. Persis seperti Habei yang membutuhkan pekerjaan sambil menyuarakan sinisme kehidupan yang dialami melalui kegelisahan yang ia anggap lucu. Ia hanya merasa dirinya lucu. Ia merasa telah menjadi guru yang diperankan orang lain dan “hanya merasa” sebagai pembaru. Padahal ia hanya “badut” betulan saja, yang “terluka” dan masih perlu membuka pikirannya, memperbarui dirinya sebelum menolong bangsanya.
Semua orang punya pilihan: menjadi badut atau pembaru. Mendiang Margareth Tatcher yang hari ini dimakamkan mungkin tak akan dikenang sebagai pemimpin besar, kalau penulis naskah pidatonya lupa menyelipkan quotes dari Abraham Lincoln berikut ini dalam sambutan perdananya di tahun 1975: “You cannot strengthen the weak by weakening the strong”. Sejak membaca quotes itu Thatcher berujar, “It goes wherever I go.”
Rhenald Kasali
Founder Rumah Perubahan